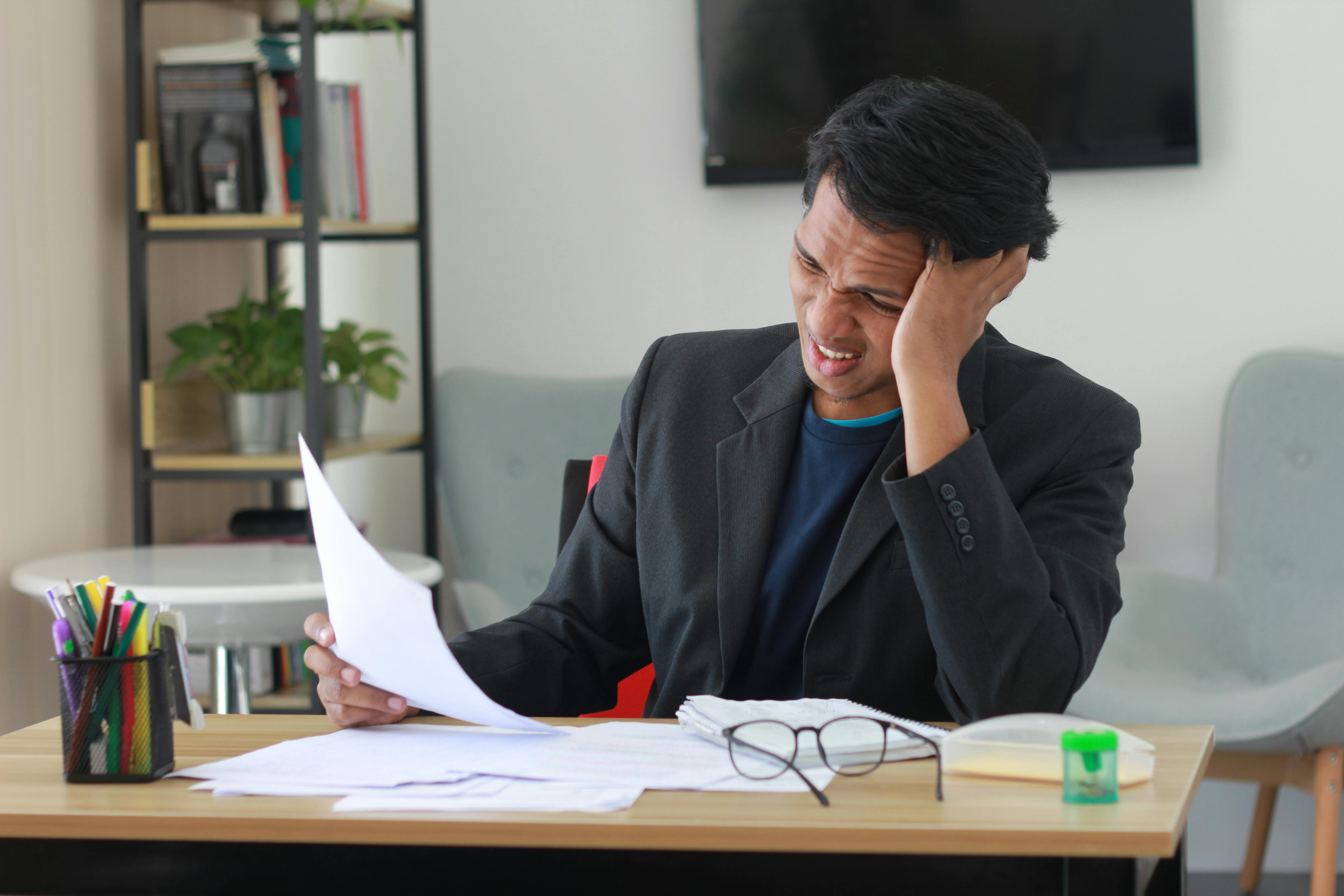
Bicara soal pekerjaan, setiap orang ingin memiliki suatu pekerjaan yang baik. Namun, bagaimana suatu pekerjaan dapat dikatakan baik? Apakah pekerjaan dengan gaji yang besar atau pekerjaan dengan durasi waktu yang tidak sedikit?
Berbagai jenis pekerjaan tentunya memiliki jam produktif yang berbeda. Setiap pekerjaan juga pasti memiliki tekanan dan tantangan yang berbeda bagi para pekerjanya. Bagaimana jika seseorang mendapatkan berbagai dorongan untuk menghabiskan waktu bekerja dan menghiraukan waktu istirahat? Atau hal tersebut merupakan upaya untuk naik jabatan yang lebih tinggi?
Bekerja tanpa mengenal waktu mungkin bukan hal baru bagi sebagian penduduk di Indonesia. Para pendahulu kita dan bahkan orang tua kita pun bekerja keras tak kenal waktu demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hustle culture atau workaholic dapat menjadi istilah lain dari fenomena tersebut. Ya, hustle culture atau workaholic adalah kondisi ketika seseorang yang memiliki ambisi atau bekerja keras, namun menghiraukan waktu istirahat.
Hal tersebut juga disampaikan pada buku yang berjudul “Confessions of workaholic: the facts about work addiction” pada tahun 1971 oleh Wayne Oates, para pekerja khususnya pada generasi milenial berasumsi bahwa keberhasilan diri dinilai dari seberapa keras mereka menghabiskan waktu untuk bekerja.
Fenomena hustle culture kembali bangkit menjadi perbincangan sejak masa pandemi, yang menyita banyak waktu produktif secara daring. Tak dapat dimungkiri, di zaman serba digital berbagai aktivitas dapat dilakukan tanpa mengenal ruang dan waktu. Mulai dari pelajar yang melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh maupun pekerja yang menyelesaikan tanggung jawab secara online.
Hustle culture tidak hanya terjangkit pada pekerja, namun mahasiswa juga menjadi korban. Mahasiswa dengan berbagai organisasi yang diikuti dan kewajiban menyelesaikan program studi yang dilakukan tanpa henti. Generasi milenial maupun generasi z mungkin beranggapan bahwa ambisi sebagai workaholic sebagai upaya efektif dalam meraih karier impian dan kesuksesan.
Perlu diketahui, bekerja dengan mengesampingkan waktu istirahat akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Berdasarkan penelitian Current Cardiology Reports tahun 2018, dikatakan bahwa seseorang yang memiliki pola waktu bekerja berlebih atau sekitar 50 jam per minggu dapat beresiko penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular seperti serangan jantung dan jantung koroner.
Selain itu, dampak bagi kesehatan mental seperti menguras banyak kortisol akibat stres berlebihan atau sebagai pemicu depresi. Dilansir dari Headversity, gila kerja dapat menurunkan tingkat produktivitas dan kreativitas seseorang. Bekerja dengan intensitas waktu yang tinggi juga dapat berpengaruh terhadap kualitas kinerja dan kehilangan work life balance itu sendiri.
Oleh karena itu, penting menjaga keseimbangan waktu bekerja dengan waktu istirahat atau hanya sekadar memenuhi kesenangan pribadi atau berolahraga. Hal tersebut efektif untuk tetap menjaga kesejahteraan diri. Penting dalam mengutamakan kesehatan dibandingkan dengan mengejar standar sosial yang tidak ada habisnya.
Penulis: Didya Nur Salamah
Comments